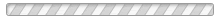| Abstrak/Abstract |
Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pemanfaatan minyak dan gas bumi, terutama dari sektor hilir. Indonesia sendiri telah memiliki Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) yang secara garis besar mengatur tentang usaha hulu dan hilir migas. Namun seiring perkembangan zaman, UU tersebut dianggap kurang relevan karena politik hukumnya hanya terfokus terhadap usaha hulu yang mengutamakan eksplorasi dan eksploitasi. Selain itu, meskipun telah terdapat pengaturan, perkembangan-perkembangan pada sektor hilir, misalnya perkembangan usaha penunjang, permintaan insentif dan lain sebagainya belum dapat diakomodasi. Adanya keterbatasan pengaturan yang tidak diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan suatu ketidakpastian hukum terhadap sektor hilir. Selain itu, BPH Migas sebagai lembaga independen yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan amanah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, pada kenyataannya memiliki kewenangan yang cukup terbatas. Salah satu penyebabnya adalah karena fungsi pengawasan yang tidak terintegrasi dengan baik, ditambah lagi tidak terjadi desentarlisasi fungsi pengawasan ke organ terbawah.
Kegiatan hilir migas merupakan sektor yang kompleks dan memiliki beragam isu-isu strategis. Berbagai isu tersebut secara komprehensif dikelompokkan ke dalam 4 cluster isu strategis yaitu: kelembagaan atau good governance, kemandirian dan ketahanan energi nasional, penggerak perekonomian serta kepastian hukum dan penyederhanaan regulasi. Berbagai isu strategis tersebut selanjutnya perlu untuk dikaji secara lebih mendalam agar permasalahan-permasalahan strategis di sektor hilir migas tidak tertinggalkan dalam RUU Minyak dan Gas Bumi pada masa yang akan datang. Hasil kajian tersebut juga diharapkan dapat menguatkan kelembagaan BPH Migas guna menjawab filosofi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan menjalankan kewajiban Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Selain itu, diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) berdampak pula terhadap ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Pengaturan perubahan UU Migas di dalam UU Cipta Kerja diatur dalam Pasal 40 UU Cipta Kerja. Perubahan UU Migas melalui UU Cipta Kerja diharapkan mampu memperkuat ketahanan dan kemandirian energi di Wilayah NKRI. UU Migas harus memberikan kepastian berusaha dan berinvestasi serta kepastian hukum untuk mendukung industri migas agar lebih efisien, transparan, sederhana dan berkeadilan serta berkelanjutan.
Melalui UU Cipta Kerja, Pasal 5 UU Migas diubah dengan menambahkan ketentuan yang berbunyi: Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Berdasarkan Naskah Akademis UU Cipta Kerja, alasan perubahan adalah semata-mata untuk melakukan penyederhanaan izin dimana hanya dengan satu izin pelaku usaha di bidang hilir mendapat berbagai hak usaha. Potensi implikasi untuk kegiatan usaha hilir yaitu diharapkan adanya penyederhanaan perizinan dan pengawasan yang lebih ketat.
Sebelumnya dalam Pasal 23 ayat (1) UU Migas dikatakan bahwa Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. Lebih detail dalam peraturan turunannya, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004, Izin Usaha diberikan kepada Badan Usaha oleh Menteri yang membidangi Minyak dan Gas Bumi, untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Perubahan Pasal 5 UU Migas di UU Cipta Kerja di atas bisa dikatakan mempertegas kekuasaan Presiden di mana perizinan berusaha dari pemerintah pusat dan sejalan dengan semangat sentralisasi izin di semua sektor usaha yang diatur dalam UU Cipta Kerja.
Perizinan adalah suatu proses pemberian legalitas secara administrasi yang digunakan sebagai dasar kegiatan usaha. Menurut Pasal 1 angka 20 UU Migas, izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba. Dalam kegiatan usaha migas ini, pembinaan dilaksanakan oleh Pemerintah dengan cermat, transparan, dan adil. Sedangkan pengawasan dilaksanakan oleh kementerian yang bidang tugas dan kewenangannya di bidang minyak dan gas bumi atau kementerian lain yang terkait. Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur.
Selama ini berdasarkan Pasal 23 UU Migas mengatur bahwa kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah yang berjumlah empat izin usaha. Empat izin usaha ini terdiri dari izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin usaha niaga. Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin usaha ini biasanya memuat nama penyelenggara, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan pengusahaan dan syarat-syarat teknis.
Dalam UU Cipta Kerja, terdapat perubahan yang cukup fundamental pada jumlah izin di sektor hilir. Dalam rangka penyederhanaan izin, pelaku usaha yang bergerak di sektor hilir diperbolehkan mendapatkan satu izin usaha kegiatan usaha hilir untuk seluruh kegiatan usaha pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Berdasar Naskah Akademisnya, pengaturan penegasan Izin Usaha Hilir dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang diberikan izin pengusahaannya. Selain itu, kegiatan usaha sektor hilir baik pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, maupun niaga dapat dilakukan secara terintegrasi atau tidak teritegrasi. Proses perizinan usaha hilir migas wajib terintegrasi dengan sistem Perizinan Berusaha, terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS). UU Cipta Kerja ini juga mengatur Perizinan Berbasis Risiko/Risk-based Licencing sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 UU Cipta Kerja.
Pada UU CK terdapat ketentuan baru Pasal 23A yang disisipkan antara Pasal 23 dan 24 UU Migas. Dari segi substansi pasal, pengaturan didalamnya berkorelasi dengan Pasal 53 yang mengatur mengenai ketentuan pidana terhadap kegiatan usaha hilir tanpa izin. Pasal 23A sengaja masukan untuk menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium atau meletakannya dalam fungsi subsider. Ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia, yang mengatakan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum. Jika asas ini digunakan maka badan usaha yang melakukan pelanggaran karena melakukan kegiatan usaha tanpa izin dan telah melaksanakan sanksi administratif, maka ia akan lepas dari delik pidana. Implementasi ultimum remedium ini dapat mengakomodasi kepentingan pelaku tindak pidana, mengingat sanksi pidana tersebut sifatnya keras. Seharusnya diusahakan menjadi jalan terakhir setelah sanksi lainnya dirasa sudah tidak dapat digunakan lagi.
Meskipun sudah ada Pasal 23A, ketentuan ini tidak secara mutlak memberlakukan asas ultimum remedium sepanjang tindakan tersebut mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan. Masih dimungkinkan pengenaan pidana berdasarkan Pasal 53 pada kegiatan usaha hilir yang tanpa izin dan berdampak negatif. Dalam perkembangannya, penerapan ultimum remedium yang mutlak ini banyak mengalami kendala, salah satunya apabila perbuatan tersebut dianggap benar-benar merugikan kepentingan negara maupun rakyat pada umumnya dan menciderai rasa keadilan, menurut Undang-Undang maupun dari segi sosial masyarakat, maka sanksi pidanalah yang menjadi pilihan utama (primum remedium). Senada dengan pendapat dari H.G de Bunt dalam bukunya strafrechtelijke handhaving van miliue recht, hukum pidana dapat menjadi primum remidium jika korban sangat besar, tersangka/terdakwa merupakan recidivist, dan kerugian tidak dapat dipulihkan (irreparable).
Sanksi hukum administrasi, menurut J.B.J.M. ten Berge, merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi. Menurut P. de Haan, dalam HAN, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Pelanggaran di bidang perizinan bentuknya bermacam-macam yang pada umumnya sudah secara definitif tercantum dalam peraturan perundang- undangan yang menjadi dasarnya. Dalam teori, sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran perizinan ada beberapa macam yaitu Paksaan Pemerintahan (bestuurdwang), Penarikan Kembali Keputusan yang menguntungkan, Pengenaan Uang Paksa oleh Pemerintah (dwangsom), Pengenaan Denda Administratif (administratif boete). Terkait dengan sanksi ini ada beberapa kriteria yang perlu untuk diperhatikan, yaitu: 1) Unsur-unsur yang dijadikan dasar sanksi tersebut diterapkan; 2) Jenis sanksi yang dikenakan; 3) Jangka waktu pengenaan sanksi; 4) Tata cara penetapan sanksi; 5) Mekanisme pengguguran sanksi.
Dalam UU Migas, sanksi administratif terhadap Badan Usaha pemegang izin usaha hilir sudah diatur di Pasal 25. Pasal ini merupakan pasal lanjutan dan penegakan dari Pasal 23 yang mengatur izin usaha dari kegiatan usaha hilir migas. Sanksi administratif ini kemudian juga diuraikan lebih detail pada PP Kegiatan Usaha Hilir khususnya di Pasal 90. Dibandingkan dengan perubahan yang dibuat oleh UU Cipta Kerja, UU Migas terkesan lebih lunak dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu kepada Badan Usaha untuk meniadakan pelanggaran yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan sebelum pemerintah melaksanakan pencabutan Izin Usaha.
UU Cipta Kerja merubah ketentuan sanksi administratif dalam Pasal 25 ini dengan menghapuskan pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha dan memberikan toleransi terhadap Badan Usaha yang ingin memperbaiki kesalahannya. Akan tetapi perlu diingat bahwa UU Cipta Kerja mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Sanksi administratif dengan Peraturan Pemerintah. Secara umum pengawasan dan pembinaan kepada setiap izin usaha berdasarkan UU Cipta Kerja diatur di dalam Pasal 177. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kewenangannya. Dalam konteks migas, pengawasan dan pembinaan ini kemungkinan akan dilaksanakan Kementerian ESDM. Kemudian tentang sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada badan usaha pemegang izin yang menyalahgunakan peruntukan izin, pemerintah dapat mengenakan beberapa tindakan berupa: a. peringatan; b. penghentian sementara kegiatan berusaha; c. pengenaan denda administratif; d. pengenaan daya paksa polisional; e. pencabutan Lisensi/Sertifikasi/Persetujuan; dan/atau f. pencabutan Perizinan Berusaha.
UU Migas telah memberikan dasar penting kepada Pemerintah untuk menjamin ketersediaan BBM dan pemberian subsidi BBM kepada masyarakat yang berhak di seluruh wilayah NKRI. Akan tetapi pada 1 Januari 2015, Presiden Joko Widodo secara resmi menghapus subsidi BBM jenis premium , dan menetapkan subsidi tetap untuk solar sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 39 Tahun 2015 jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2016.
Dalam pengaturan eksisting, UU Migas telah memberikan larangan penyalahgunakan BBM Bersubsidi. Bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dikenakan pidana penjara maupun pidana denda. UU Cipta Kerja menambah objek di Pasal 55 UU Migas menjadi Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas. Sebelumnya, sanksi hanya dikenakan untuk penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah.
Perkembangan UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh pemerintah perlu diperhatikan dalam agar tidak ada pertentangan atau perubahan yang menimbulkan ketidakpastian usaha di sektor hilir migas. Kepastian merupakan hal yang penting dalam kegiatan usaha di bidang migas. Di sisi lain, perubahan UU Migas yang dilakukan melalui pengundangan UU Cipta Kerja masih dinilai kurang bisa mengakomodasi kebutuhan sektor hilir yang sangat dinamis. Pengarusutamaan sektor hilir migas sebenarnya telah diatur sejak tahun 2004 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah melalui PP Nomor 30 Tahun 2009 sebagai dasar pengaturan lebih lanjut mengenai usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga migas. Walaupun telah terdapat pengaturan, perkembangan sektor hilir lain seperti kelembagaan Badan Pengatur (kewenangan, anggaran dan SDM) yang mendukung perkembangan usaha hilir, kebutuhan akselerasi distribusi migas dalam konteks negara kepulauan dan lain sebagainya belum dapat diakomdasi dalam pengaturan saat ini. Keterbatasan pengaturan yang tidak diakomodir oleh peraturan perundang-undangan menyebabkan suatu ketidakpastian hukum terhadap sektor hilir. Untuk itu, pencanangan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi yang baru diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi hal-hal penting dalam sektor migas yang selama ini belum diatur.
|