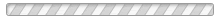| Penulis/Author |
dr. Likke Prawidya Putri, M.P.H., Ph.D. (1) ; Prof. dr. R. Detty Siti Nurdiati Z, MPH., Ph.D., Sp.OG(K). (2); Prof. dr. Indah Kartika Murni, M.Kes., Sp.A(K)., Ph.D. (3); dr. Vicka Oktaria, M.P.H., Ph.D (4); Bayu Satria Wiratama, M.P.H., Ph.D (5); Lusha Ayu Astari, S.KM., M.P.H. (6); Ichlasul Amalia (7); NILA MUNANA (8); Dr. Daniel, M.Sc. (9) |
| Abstrak/Abstract |
-Salah satu target pencapaian SDGs poin ketiga, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, adalah penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) hingga kurang dari 70 per 100,000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Data statistik Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta di tahun 2022, menunjukkan angka kematian ibu di DIY merupakan salah satu yang terendah di Indonesia, yaitu 43 per 100,000 kelahiran hidup, jauh di bawah angka nasional yaitu 189 per 100,000 kelahiran hidup. Namun demikian, angka ini masih di bawah AKI di negara berkembang lain dengan rasio bidan-perawat terhadap penduduk jauh lebih rendah, misalnya Vietnam secara nasional memiliki 1.5 bidan-perawat per 1,000 penduduk dengan angka kematian ibu 42 per 100,000, ataupun Malaysia, dengan 2.9 bidan-perawat per penduduk yang memiliki angka kematian ibu 24 per 100,000 (World Bank, 2023). Selama tahun 2021, terdapat 131 kasus kematian ibu di DIY, yang berarti terdapat 1 orang ibu hamil atau bersalin yang meninggal setiap 3 minggu. Dari angka kematian ibu tersebut, lebih dari separuh disebabkan oleh penyebab yang dapat dicegah, yaitu perdarahan dan preeklampsia (Sakinatunisa, 2023). DI Yogyakarta memiliki 23 bidan-perawat per 1,000 penduduk, dengan lebih dari 60 rumah sakit umum dan bersalin dan infrastruktur jalan yang baik. Dengan demikian DI Yogyakarta memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat menurunkan angka kematian ibu sampai ke setengah angka saat ini.
Penyebab utama dari tingginya AKI tidak hanya berasal dari satu faktor saja, melainkan merupakan hasil dari berbagai interaksi kompleks antara berbagai faktor, seperti akses terhadap pelayanan kesehatan, pengetahuan masyarakat tentang kesehatan reproduksi, serta faktor sosial dan ekonomi (Cameron et al., 2019; D'Ambruoso et al., 2010). Selama beberapa tahun terakhir, upaya untuk menurunkan AKI di Daerah Istimewa Yogyakarta telah melibatkan berbagai program mulai dari hulu ke hilir, baik yang merupakan program pemerintah pusat maupun inovasi-inovasi di DIY dan wilayahnya.
Beberapa program di ranah hulu yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil atau antenatal sesuai dengan standar, paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan per trimester (K4) serta minimal dua kali pemeriksaan dokter (K6), pemberian makanan tambahan lokal bagi ibu hamil dengan KEK, pendampingan ibu hamil oleh mahasiswa atau petugas kesehatan, serta edukasi mengenai anemia pada remaja putri (FITRIANA et al., 2020; Larasati et al., 2021). Untuk mengatasi permasalahan determinan sosial, beberapa pemerintah desa juga telah berkontribusi pada kegiatan edukasi ibu hamil misalnya dengan menyelenggarakan kelas ibu hamil, penguatan kapasitas kader untuk melakukan peran edukasi dan promosi (Handayani et al., 2020; Handayani & Kurniawati, 2023; Rahmi et al., 2017). Namun, sayangnya beberapa program tersebut masih cenderung fluktuatif. Salah satunya, cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 pada tahun 2022 di DIY berada pada peringkat ketiga terendah dibandingkan provinsi lain di Indonesia, dengan capaian 55,5%, masih jauh dibawah capaian nasional yaitu 86.2%, dan target RPJMN 2022 yaitu 90%.
Sementara itu di ranah hilir telah dilaksanakan kegiatan audit maternal perinatal yang dikaitkan dengan surveilans respons (AMPSR), dan penyusunan manual rujukan KIA. Manual rujukan KIA dirancang untuk memfasilitasi akses yang lebih cepat dan tepat kepada pelayanan kesehatan maternal yang berkualitas bagi perempuan yang mengalami komplikasi saat hamil, melahirkan, atau masa nifas. Melalui program manual rujukan ini, para ibu yang membutuhkan perawatan medis darurat atau spesialisasi dapat dirujuk dari puskesmas atau desa ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi tingkatannya, seperti rumah sakit atau pusat kesehatan lain yang dilengkapi dengan fasilitas dan tenaga medis yang sesuai. Program manual rujukan ini tidak hanya memfasilitasi proses rujukan, tetapi juga mencakup aspek pelatihan dan koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk bidan, tenaga medis di puskesmas, petugas kesehatan di tingkat kabupaten, dan rumah sakit (Dinas Kesehatan Kulon Progo, 2012). Melalui pelatihan yang terarah dan diseminasi informasi tentang prosedur rujukan yang jelas, diharapkan bahwa proses rujukan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pasien. Namun, meskipun telah dilakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas program manual rujukan, masih terdapat beberapa hambatan dalam implementasinya. Beberapa di antaranya meliputi keterbatasan sumber daya, keterlambatan dalam proses rujukan, kurangnya pemahaman tentang pentingnya rujukan yang tepat waktu, dan tantangan logistik dalam transportasi pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Berbagai intervensi yang dilakukan di ranah ‘hulu’ juga memiliki keterbatasan, antara
Sehingga penting untuk diakui bahwa upaya penurunan AKI dari hulu dan hilir dapat dioptimalkan untuk menurunkan angka kematian ibu dengan identifikasi akar permasalahan yang tepat. Penelaahan akar masalah ini dapat mendukung identifikasi dan pemetaan pemangku kebijakan serta lintas sektor. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci dalam merumuskan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk menangani masalah kesehatan reproduksi, termasuk penurunan AKI.
Dalam konteks ini, pendalaman pemahaman dan penelaahan tentang akar masalah AKI serta strategi pencegahannya menjadi hal yang sangat krusial dalam menentukan strategi yang perlu dilakukan. Penggunaan alat analisis seperti Causal Loop Diagram dapat membantu dalam mengidentifikasi dan memahami secara lebih mendalam interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi AKI, sehingga dapat merumuskan strategi intervensi yang lebih tepat sasaran dan efektif untuk mempercepat penurunan AKI di Daerah Istimewa Yogyakarta.
|